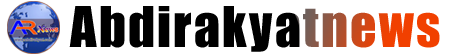[18:13, 4/10/2021] Cak Bidin: Oleh :
Umar Sholahudin
Dosen Sosiologi FISIP Universiats Wijaya Kusuma Surabaya, Kandidat Doktor FISIP Unair
Aksi terorisme sepertinya tidak pernah surut dari bumi Indonesia. Kekerasan demi kekerasan terus diproduksi dan reproduksi, laiknya spiral kekerasan. baik oleh Negara maupun masyarakat. Baik kekerasan atas nama agama, budaya, atau etnis. Setelah kasus kekerasan di Ambon, Maluku, kini muncul aksi kekerasan baru, yakni aksi terorisme berupa aksi “bom bunuh diri”. Mengutip aliran eksistensialisme Nitsche, aksi bom bunuh diri tersebut bisa fahami sebagai manifestasi dan wujud eksistensi diri pelaku dan jaringannya. Bahwa aksi dan jaringan mereka masih eksis. Eksistensi mereka ada dan diakui karena tindakannya (terorisme).
Kehidupan ini sepertinya sudah tidak ada ruang sedikitpun untuk bisa hidup aman dan nyaman dibawah naungan sikap toleransi dan saling menghargai dalam perbedaan. Kehidupan manusia selalu dibawah bayang-bayang aksi kekerasan. Kehidupan masyarakat kita ini bagaikan apa yang diungkapkan oleh Thomas Hobes sebagai “homo homini lupus”, manusia adalah srigala bagi sesamanya. Nurani kemanusiannya luntur dimakan ambisi kehewanan. Begitu mudah seorang manusia melakukan tindak kekerasan dan bahkan membunuh sesamanya. Bahkan perilaku manusia semacam ini lebih buruk dari hewan.
Itu pula yang ditunjukan pada aksi bom bunuh diri di Gereja Katedral, Makassar, Sulawesi Selatan (28/3) yang menewaskan pelakunya (diduga 2 orang), dan mengakibatkan korban luka (berat dan ringan) sebanyak 20 orang. Kasus Makasar ini semakin menambah daftar panjang kasus bom bunuh diri dan aksi terorisme di Indonesia. Dalam beberapa kasus sebelumnya, para pelaku terorisme atau bom bunuh diri menyasar aparat kepolisian atau kantor-kantor polisi, termasuk kasus di Medan.
Sebagai negeri yang beragam, khususnya beragam secara agama, masalah hubungan antar ummat agama di Indonesia belakangan ini memang sangat kompleks dan sedang mengalami ujian berat. Banyak kepentingan ekonomi, sosial dan politik yang mewarnai ketegangan tersebut. Belum lagi agama sering dijadikan alat pemecah belah atau disintegrasi, karena adanya konflik-konflik di tingkat elite dan militer. Kasus bom Makassar tersebut telah mengusik rasa solidritas, toleransi, kerukunan, dan rasa kemanusian kita sebagai bangsa serta tentunya kerukunan hidup beragama di Indonesia. Perbedaan dalam hidup bermasyarakat adalah sebuah keniscayaan yang tak bisa dihindari, baik perbedaan (pemikiran dan keyakinan) agama, kultural, politik dan sebagainya. Dalam konteks inilah, kita diuji dengan sikap kedewasaan, tasamuh, rasionalitas kita dalam menghadapi keragaman kultural tersebut.
Kasus intoleransi dan kekerasan ini tentu mengusik rasa solidaritas, rasa kemanusian kita sebagai bangsa serta tentunya kerukunan hidup beragama. Perbedaan dalam hidup bermasyarakat adalah sebuah keniscayaan yang tak bisa dihindari, baik perbedaan (pemikiran dan keyakinan) agama, kultural, politik dan sebagainya. Anarkhisme dan kekerasan atas nama apapun dan dalam bentuk apapun sangat tidak dibenarkan dalam kehidupan sosial-agama kita yang demokratis. Dialog interaktif dengan niatan yang positif adalah cara yang paling elegan meminimalisir ketegangan dan menyelesaikan persoalan perbedaan di antara kita.
Direktur Pelaksana Pengembangan Pesantren dan Masyarakat, Masdar Mas’udi, pernah mengatkaan :”saya lebih suka hidup dengan orang yang berbeda agama tetapi tidak tertekan dariapda hidup bersama dengan orang yang seagama tetapi tertekan”. Statement ini setidaknya bisa menjadi introspeksi dan koreksi ke internal kita masing-masing sebagai pemeluk agama. Anarkhisme dan kekerasan bukanlah inti dasar ajaran agama.
Menurut Mark Taylor, sebagaimana dikutip Bambang Sugiarto (1998)- seiring dengan perkembangan zaman, keberadaan agama sering dihadapkan pada tantangan dan kendala yang sering kali terus berproduksi tanpa adanya solusi yang tuntas. Beberapa tantangan dan kendala itu di antaranya, Pertama, kemelut dalam tubuh masing-masing agama sendiri seringkali memproyeksi keluar. Sikap agresif berlebihan terhadap pemeluk agama lain seringkali merupakan ungkapan yang tak disadari dari chaos dan ketegangan dalam tubuh agama itu sendiri.
Kedua, paham tentang kemutaklan Tuhan -yang umumnya dianut hampir semua agama besar- juga memudahkan orang untuk mengidentikan kemutlakan itu dengan kemutlakan agamanya. Keyakinan macam ini, biarpun masuk akal, secara psikologis memudahkan orang untuk melegitimasi segala bentuk tindaka kekerasannya sebagai yang “dikehendaki oleh Tuhan”.
Ketiga, ada keyakinan suci di internal pemeluk agama, bahwa segala tindakan macam itu justru akan diganjari pahala oleh Tuhan. Keyakinan “mutlak” ini kemudian menyebabkan kekeraan terharap pemuluk agama lain justru merupakan bagian dari kekuatan moral. Tentunya ini adalah sebuah ironi yang bukan saja kontradiktif, tetapi juga berbahaya bukan hanya bagi pemuluk agama laian, tetepi juga bagi agamanya sendiri. Citra agama sebagai ajaran yang damai, santun, lemah-lembut, kasih sayang dan nilai-nilai moral dan suci lainnya menjadi “terkontaminasi” oleh perilaku sebagian pemuluk agama yang keliru, puritan dan skriptualitik.
Keempat, dengan naik-daunnya posisi agama dalam konstelasi peradaban kini, agama pun menjadi rawan untuk ditunggangi kepentingan-kepentingan politik, ekonomi, cultural keleompok-kelompok tertentu atau pribadi . Dan bila ini terjadi, maka bahaya akan segera datang, yakni integrasi agama terancam akan hancur. Alih-alih akan menjadi suatu terapi solutif bagi kemelut hingar-bingar modernitas, agama justru akan dirasa sebagai penyakit berbaha, alih-alih menjadi berkah, ia tampil justru sebagai kutukan.
Tiga Solusi
Ian G Barbour dalam karyanya When Science Meet Religion menawarkan tiga solusi mengatasi konflik dalam pemikiran keagamaan. Pertama, melalui independensi, yakni melalui suatu pemahaman, pada dasarnya setiap pemeluk agama memiliki kebenaran dan penafsiran sendiri-sendiri. Otoritas kebenaran hanya ada dalam pemikiran umat beragama dan orang tidak boleh memaksakan dan merasa agamanya paling benar. Karena itu, sikap menghargai dan menghormati perbedaan pemikiraan keagaaman perlu dikedepankan. Dari situ, kaum beragama dapat hidup rukun berdampingan meski dalam perbedaan pemikiran dan keyakinan.
Kedua, melalui dialog antaragama untuk saling menyapa agar muncul hubungan yang harmonis dan menghilangkan klaim paling benar. Kehadiran tokoh tertentu harusnya dijadikan bagian dari dialog dalam wilayah pemikiran keagamaan.
Ketiga, Terkait kebebasan beragama, berpikir, berpendapat, mengharuskan negara bersikap dan bertindak adil pada semua penganut agama dan keyakinan yang hidup di negeri ini. Negara tidak boleh bersikap memihak terhadap kelompok keagamaan tertentu dan berbuat diskriminatif terhadap kelompok lainnya.
Dalam konteks yang lebih luas, setiap pemeluk agama perlu membangun dan mengembangkan pola hubungan beragama yang inkluisf yang didasari dengan sikap husnudzon. Selain itu, langkah lainnya, perlu adanya dialog intra-religious maupun inter-religious dialog ke dalam maupun keluar perspektif agama masing-masing. Perlu ada dialog interaktif yang setara.dan tentunya didasari pada niat dan prasangka positif. Selain upaya ini, perlu adanya gerakan di internal agama untuk melakukan gerakan revitalisasi peran organisasi agama yang lebih aktual dan kontekstual.
——— * ———-
[18:14, 4/10/2021] Cak Bidin: Oleh :
Umar Sholahudin
Dosen Sosiologi FISIP Universiats Wijaya Kusuma Surabaya, Kandidat Doktor FISIP Unair
Aksi terorisme sepertinya tidak pernah surut dari bumi Indonesia. Kekerasan demi kekerasan terus diproduksi dan reproduksi, laiknya spiral kekerasan. baik oleh Negara maupun masyarakat. Baik kekerasan atas nama agama, budaya, atau etnis. Setelah kasus kekerasan di Ambon, Maluku, kini muncul aksi kekerasan baru, yakni aksi terorisme berupa aksi “bom bunuh diri”. Mengutip aliran eksistensialisme Nitsche, aksi bom bunuh diri tersebut bisa fahami sebagai manifestasi dan wujud eksistensi diri pelaku dan jaringannya. Bahwa aksi dan jaringan mereka masih eksis. Eksistensi mereka ada dan diakui karena tindakannya (terorisme).
Kehidupan ini sepertinya sudah tidak ada ruang sedikitpun untuk bisa hidup aman dan nyaman dibawah naungan sikap toleransi dan saling menghargai dalam perbedaan. Kehidupan manusia selalu dibawah bayang-bayang aksi kekerasan. Kehidupan masyarakat kita ini bagaikan apa yang diungkapkan oleh Thomas Hobes sebagai “homo homini lupus”, manusia adalah srigala bagi sesamanya. Nurani kemanusiannya luntur dimakan ambisi kehewanan. Begitu mudah seorang manusia melakukan tindak kekerasan dan bahkan membunuh sesamanya. Bahkan perilaku manusia semacam ini lebih buruk dari hewan.
Itu pula yang ditunjukan pada aksi bom bunuh diri di Gereja Katedral, Makassar, Sulawesi Selatan (28/3) yang menewaskan pelakunya (diduga 2 orang), dan mengakibatkan korban luka (berat dan ringan) sebanyak 20 orang. Kasus Makasar ini semakin menambah daftar panjang kasus bom bunuh diri dan aksi terorisme di Indonesia. Dalam beberapa kasus sebelumnya, para pelaku terorisme atau bom bunuh diri menyasar aparat kepolisian atau kantor-kantor polisi, termasuk kasus di Medan.
Sebagai negeri yang beragam, khususnya beragam secara agama, masalah hubungan antar ummat agama di Indonesia belakangan ini memang sangat kompleks dan sedang mengalami ujian berat. Banyak kepentingan ekonomi, sosial dan politik yang mewarnai ketegangan tersebut. Belum lagi agama sering dijadikan alat pemecah belah atau disintegrasi, karena adanya konflik-konflik di tingkat elite dan militer. Kasus bom Makassar tersebut telah mengusik rasa solidritas, toleransi, kerukunan, dan rasa kemanusian kita sebagai bangsa serta tentunya kerukunan hidup beragama di Indonesia. Perbedaan dalam hidup bermasyarakat adalah sebuah keniscayaan yang tak bisa dihindari, baik perbedaan (pemikiran dan keyakinan) agama, kultural, politik dan sebagainya. Dalam konteks inilah, kita diuji dengan sikap kedewasaan, tasamuh, rasionalitas kita dalam menghadapi keragaman kultural tersebut.
Kasus intoleransi dan kekerasan ini tentu mengusik rasa solidaritas, rasa kemanusian kita sebagai bangsa serta tentunya kerukunan hidup beragama. Perbedaan dalam hidup bermasyarakat adalah sebuah keniscayaan yang tak bisa dihindari, baik perbedaan (pemikiran dan keyakinan) agama, kultural, politik dan sebagainya. Anarkhisme dan kekerasan atas nama apapun dan dalam bentuk apapun sangat tidak dibenarkan dalam kehidupan sosial-agama kita yang demokratis. Dialog interaktif dengan niatan yang positif adalah cara yang paling elegan meminimalisir ketegangan dan menyelesaikan persoalan perbedaan di antara kita.
Direktur Pelaksana Pengembangan Pesantren dan Masyarakat, Masdar Mas’udi, pernah mengatkaan :”saya lebih suka hidup dengan orang yang berbeda agama tetapi tidak tertekan dariapda hidup bersama dengan orang yang seagama tetapi tertekan”. Statement ini setidaknya bisa menjadi introspeksi dan koreksi ke internal kita masing-masing sebagai pemeluk agama. Anarkhisme dan kekerasan bukanlah inti dasar ajaran agama.
Menurut Mark Taylor, sebagaimana dikutip Bambang Sugiarto (1998)- seiring dengan perkembangan zaman, keberadaan agama sering dihadapkan pada tantangan dan kendala yang sering kali terus berproduksi tanpa adanya solusi yang tuntas. Beberapa tantangan dan kendala itu di antaranya, Pertama, kemelut dalam tubuh masing-masing agama sendiri seringkali memproyeksi keluar. Sikap agresif berlebihan terhadap pemeluk agama lain seringkali merupakan ungkapan yang tak disadari dari chaos dan ketegangan dalam tubuh agama itu sendiri.
Kedua, paham tentang kemutaklan Tuhan -yang umumnya dianut hampir semua agama besar- juga memudahkan orang untuk mengidentikan kemutlakan itu dengan kemutlakan agamanya. Keyakinan macam ini, biarpun masuk akal, secara psikologis memudahkan orang untuk melegitimasi segala bentuk tindaka kekerasannya sebagai yang “dikehendaki oleh Tuhan”.
Ketiga, ada keyakinan suci di internal pemeluk agama, bahwa segala tindakan macam itu justru akan diganjari pahala oleh Tuhan. Keyakinan “mutlak” ini kemudian menyebabkan kekeraan terharap pemuluk agama lain justru merupakan bagian dari kekuatan moral. Tentunya ini adalah sebuah ironi yang bukan saja kontradiktif, tetapi juga berbahaya bukan hanya bagi pemuluk agama laian, tetepi juga bagi agamanya sendiri. Citra agama sebagai ajaran yang damai, santun, lemah-lembut, kasih sayang dan nilai-nilai moral dan suci lainnya menjadi “terkontaminasi” oleh perilaku sebagian pemuluk agama yang keliru, puritan dan skriptualitik.
Keempat, dengan naik-daunnya posisi agama dalam konstelasi peradaban kini, agama pun menjadi rawan untuk ditunggangi kepentingan-kepentingan politik, ekonomi, cultural keleompok-kelompok tertentu atau pribadi . Dan bila ini terjadi, maka bahaya akan segera datang, yakni integrasi agama terancam akan hancur. Alih-alih akan menjadi suatu terapi solutif bagi kemelut hingar-bingar modernitas, agama justru akan dirasa sebagai penyakit berbaha, alih-alih menjadi berkah, ia tampil justru sebagai kutukan.
Tiga Solusi
Ian G Barbour dalam karyanya When Science Meet Religion menawarkan tiga solusi mengatasi konflik dalam pemikiran keagamaan. Pertama, melalui independensi, yakni melalui suatu pemahaman, pada dasarnya setiap pemeluk agama memiliki kebenaran dan penafsiran sendiri-sendiri. Otoritas kebenaran hanya ada dalam pemikiran umat beragama dan orang tidak boleh memaksakan dan merasa agamanya paling benar. Karena itu, sikap menghargai dan menghormati perbedaan pemikiraan keagaaman perlu dikedepankan. Dari situ, kaum beragama dapat hidup rukun berdampingan meski dalam perbedaan pemikiran dan keyakinan.
Kedua, melalui dialog antaragama untuk saling menyapa agar muncul hubungan yang harmonis dan menghilangkan klaim paling benar. Kehadiran tokoh tertentu harusnya dijadikan bagian dari dialog dalam wilayah pemikiran keagamaan.
Ketiga, Terkait kebebasan beragama, berpikir, berpendapat, mengharuskan negara bersikap dan bertindak adil pada semua penganut agama dan keyakinan yang hidup di negeri ini. Negara tidak boleh bersikap memihak terhadap kelompok keagamaan tertentu dan berbuat diskriminatif terhadap kelompok lainnya.
Dalam konteks yang lebih luas, setiap pemeluk agama perlu membangun dan mengembangkan pola hubungan beragama yang inkluisf yang didasari dengan sikap husnudzon. Selain itu, langkah lainnya, perlu adanya dialog intra-religious maupun inter-religious dialog ke dalam maupun keluar perspektif agama masing-masing. Perlu ada dialog interaktif yang setara.dan tentunya didasari pada niat dan prasangka positif. Selain upaya ini, perlu adanya gerakan di internal agama untuk melakukan gerakan revitalisasi peran organisasi agama yang lebih aktual dan kontekstual.